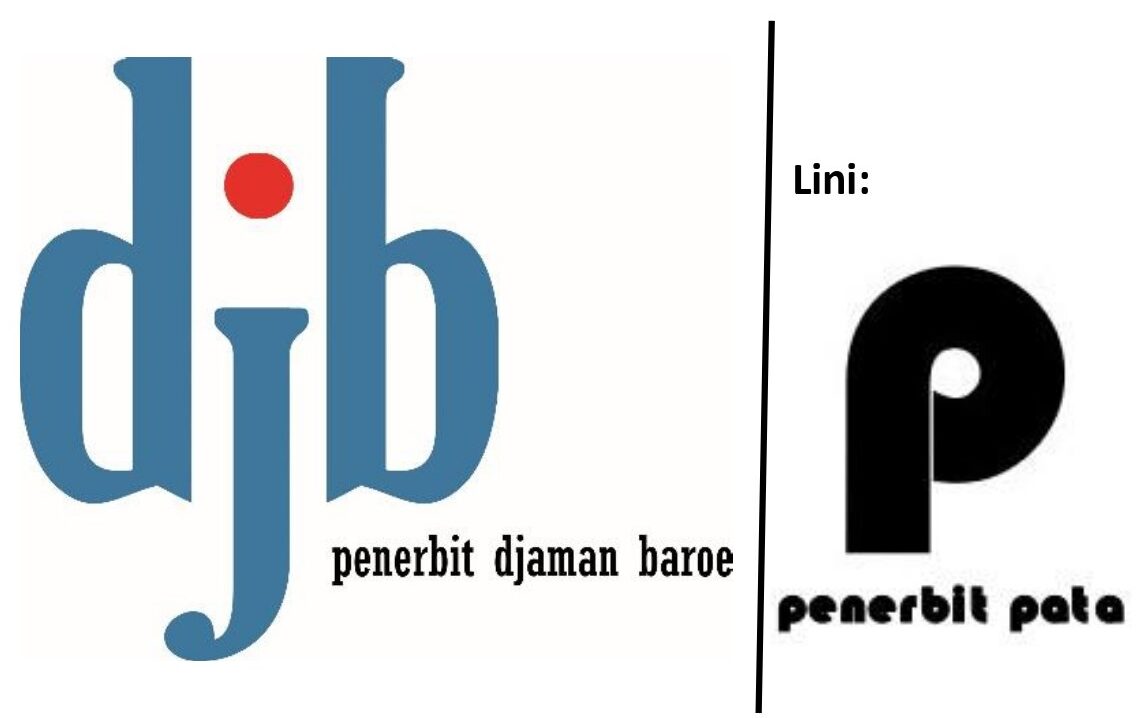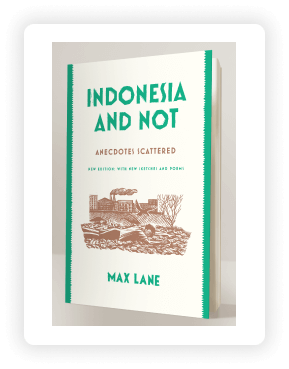A. Max Lane, Malapetaka di Indonesia: Sebuah Esei Renungan tentang Pengalaman Sejarah Gerakan Kiri
- Meneropong Masa Silam Kiri Indonesia
- Oleh Bonnie Triyana – 24 Agt 2017
- Sumber: https://historia.id/politik/articles/meneropong-masa-silam-kiri-indonesia-6jogb/page/1
- MALAPETAKA DI INDONESIA: SEBUAH REFLEKSI ATAS PENGALAMAN SEJARAH GERAKAN KIRI
- Harry Isra M. – 27 April 2015
- Sumber: https://lawunhas.wordpress.com/2015/04/27/malapetaka-di-indonesia-sebuah-refleksi-atas-pengalaman-sejarah-gerakan-kiri/
“…
Apa yang menyebabkan gerakan kiri di Indonesia berkembang pesat? Khususnya pasca kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno dan secara resmi diakui Belanda pada tahun 1949. Penyebab utamanya adalah lemahnya kelas pemilik properti atau borjuis Indonesia pada masa itu. Kelas borjuis Indonesia merupakan kelas yang lemah, kurang berkembang dan rapuh, dengan secuil organisasi politik, bahkan nyaris tanpa perkembangan budaya nasional dan bobot sosial[i].
…
Sementara itu, hegemoni baru yang diciptakan gerakan kiri Indonesia semakin melebar dengan basis ideologi perjuangan melawan kolonialisme/imperialisme, keharusan berbuat aktif dan keadilan sosial. Dari sini, proses radikalisasi massa menyebar keseluruh negeri dengan berbagai macam formasi kelompok sosialis dan komunis, juga organ buruh dan tani[ii].
Akibat pengaruh radikalisasi massa yang begitu cepat, kelompok sipil dan borjuis menggantungkan diri kepada kelompok militer anti-komunis sebagai basis pertahanannya, yang juga mendapatkan sokongan dari pemerintah Amerika Serikat melalui agen CIA. Benturan antar kedua kelompok ini, sayap kiri dan militer, mendapatkan momentum awalnya pada tahun 1947 sampai 1948, yang betitik puncak pada bentrokan besar di Madiun. PKI berusaha merebut kota Madiun untuk dijadikan pemerintahan baru yang radikal, sementara militer berhasil menghentikannya melakukan pengganyangan terhadap PKI, menangkap para pimpinannya.
…
Walaupun Soekarno, PKI dan aliansinya berhasil mengorganisasi massa hingga kurang lebih 20 juta orang, kubu militer dan sayap kanan juga tak kalah kuatnya dalam mengkonsolidasikan kekuatannya dan membeberkan sikap reaksionernya terhadap kubu sayap kiri. Pertarungan antara sayap kiri dan sayap kanan sesungguhnya merupakan pertarungan antar kelompok nirsenjata melawan kelompok bersenjata. Berikut catatan kronologis Max Lane atas tindakan militer untuk menghancurkan gerakan kiri Indonesia:
- 1951:Tentara mengklaim akan adanya kup dan memakai hal itu sebagai alasan untuk menangkap 2000 anggota PKI. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka dibebaskan tanpa proses pengadilan[iii].
- 1952:Tentara mengepung Istana Presiden dengan meriam dan menuntut Soekarno untuk membubarkan pemerintahan. Soekarno menolak tegas dan berhasil meredam pemberontakan tersebut[iv].
- 1956-1957: Elemen-elemen sayap kanan di dalam tubuh militer merebut kekuasaan atas sebagian provinsi dan menangkap para aktivis serikat pekerja dan sayap kiri. Kelompok ini kemudian membentuk PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang didukung oleh partai politik anti-komunis terutama Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan PSI (Partai Sosialis Indonesia), juga oleh pemerintah Amerika Serikat.
…
Kontradiksi Dalam Taktik
Pada tahun 1959, Soekarno secara resmi mengumumkan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Manuver tersebut dilakukan Soekarno agar dapat menunjuk jajaran kabinetnya secara presedensial dan untuk mendapatkan ruang yang lebih luas bagi arahan-arahan kepresidenan[vi].
Perubahan penting dari model pemerintahan ini ialah terbentuknya tatanan parlemen baru yang mampu mengkompromikan wakil-wakil partai politik, serikat dagang, maupun kelompok tani. Namun disatu sisi, Soekarno mau tak mau harus pula mengakui keberadaan angkatan bersenjata atau militer, yang menyebabkan keterlibatannya secara langsung dalam kancah politik.
Disamping itu, Soekarno juga mengambil keputusan atas pelarangan dua partai politik: Masyumi dan PSI, dimana tokoh utama keduanya, terlibat dalam pemberontakan bersenjata 1956-1958 dan pembentukan PRRI. Ada pula larangan terhadap Manikebu (Manifestasi Kebudayaan) yang dihuni oleh sekelompok seniman dan intelektual anti-kiri. Hal ini bukan hanya kontradiktif dengan nilai demokrasi itu sendiri, namun juga berakibat pada semakin kuatnya pengkonsolidasian kubu sayap kanan “dibawah tanah” yang dipimpin Angkatan Darat. Pada tahun-tahun setelahnya, PKI juga menuntut pelarangan atau peminggiran partai-partai kanan seperti Murba dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menjalin hubungan erat dengan Masyumi, yang belakangan menjadi pendukung basis kediktatoran Soeharto[vii].
Keputusan lain yang diambil oleh Soekarno adalah pemberlakuan Keadaan Darurat Militer (SOB) yang berlaku hingga tahun 1962. Dampaknya, militer tidak hanya masuk ke gelanggang politik dan menjadi dewan eksekutif pemerintahan regional, mereka juga merebut kontrol atas perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi pada tahun 1956-1958 atau masa ketika para pekerja mulai berada dibawah kepemimpinan kelompok kiri[viii] . Lebih dari itu, perusahaan yang berhasil mereka rebut menjadi lahan korupsi sekaligus memperkuat ikatan antara pejabat militer dan para kapitalis sipil.
…
Malapetaka pun terjadi. Sebelum biro khusus Aidit menahan para jenderal, jenderal tersebut telah terlebih dahulu dibunuh. Akibatnya, konspirasi retuling tersebut dijadikan sebagai dalih dan kesempatan Angkatan Bersenjata untuk memusnahkan komunisme. Soeharto mengutuk keras peristiwa tersebut dan menuding PKI harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia mengisolasi Soekarno sekaligus menjadi presiden Republik Indonesia. pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan gagalnya percobaan retuling Angkatan Bersenjata yang dilakukan biro khusus Aidit?
Menurut Max Lane, ada dua jawaban dari pertanayaan tersebut. Pertama, Aidit terlalu yakin atas perhitungan Sjam bahwa ia telah berhasil merekrut sepertiga dari Angkatan Bersenjata, khususnya Angkatan Laut dan Darat. Kedua, boleh jadi ia percaya bahwa keseluruhan operasi—dengan cara menahan dan menghadapkan para petinggi Angkatan Bersenjata ke Soekarno—akan menjadi aksi sederhana, cepat dan berjalan mulus[xvi]. Pada kenyataannya, aksi biro khusus Aidit telah terbaca oleh pihak Angkatan Darat yang telah berkonsolidasi erat dengan partai-partai kontra Soekarno dan PKI.
…
Selama kurang lebih 33 tahun Soeharto memimpin, segala kenangan yang berbau tentang komunisme dan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme dihapuskan. Masyarakat Indonesia seperti hidup tanpa kenangan, tanpa masa lalu, mirip dengan masyarakat dalam film The Giver. Apa hikmah dari semua itu? Bagaimana gerakan kiri dalam melawan penjajahan tingkat lanjut saat ini? Apa saja kontradiksinya? Dan apa yang harus kita perbuat? Menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua yang menginginkan keadilan sosial di negeri ini.”
- Malapetaka ‘65 yang Belum Usai
Achmad Choirudin – 15 Agustus 2012
Sumber: https://indoprogress.com/2012/08/malapetaka-65-yang-belum-usai/
“…
Sebagai indonesianis yang menaruh perhatian pada gerakan kiri, di sini Max sedari awal menegaskan keberpihakannya kepada gerakan kiri. Ada dua asumsi yang mendasari keberpihakannya. Pertama, ia melihat penghancuran gerakan kiri di Indonesia dengan pembantaian, penyiksaan, penangkapan, pelarangan berpolitik terhadap ratusan ribu warga negara Indonesia, hingga pemutusan perkembangan keilmuannya, merupakan ‘kriminalitas yang tidak berperikemanusiaan atau perbuatan barbar’ (hlm. viii). Kedua, Max adalah orang yang berideologi kiri. Dalam artikel ‘Soekarno: Pemersatu atau Pembelah’ di Bagian II buku ini, ia menegaskan, ‘Baik sebagai seorang akademisi yang ‘indonesianis’ maupun sebagai warga dunia yang berkewajiban berideologi, saya menyatakan sebelumnya bahwa saya termasuk orang yang sangat menghargai kepemimpinan Soekarno serta pikirannya, meskipun saya juga berpendapat dia bukan manusia sempurna: pernah juga melakukan kekeliruan dan kadang-kadang analisa yang salah’ (hlm. 83–84).
Max tak menghindarkan kritiknya atas ragam kontradiksi yang diidap oleh gerakan kiri itu sendiri. Bisa dibilang, sebagian besar ulasan buku ini berisi kritik tajam terhadap strategi-strategi politik Soekarno dan PKI yang kontrapoduktif. Ada dua poin utama yang dicacat Max Lane di sini: taktik demokrasi terpimpin beserta jebakan retuling. Keduanya berkaitan. Kegagalan Badan Konstituante untuk memperoleh dukungan penuh parlemen dalam membahas undang-undang baru dimanfaatkan Soekarno untuk memberlakukan demokrasi terpimpin melalui dekritnya 5 Juli 1959. Dengan strategi ‘sentralistik’ ini, Soekarno memang berhasil mengkompromikan pelbagai partai politik di parlemen sekaligus memobilisasi kekuatan-kekuatan massa dengan tujuan organisasi politik, nasional dan tunggal dalam platform sosialisme bisa cepat terbangun.
…
Sebagai intelektual yang memihak gerakan kiri, secara tegas kritik Max atas strategi-strategi yang kontraproduktif itu bisa dibilang konstruktif. Secara dialektis, ia tetap mengemukakan keberhasilan-keberhasilan gerakan kiri di tengah strategi-strategi yang kontraproduktif. Meski tak demokratis, Max tetap mencatat, selama demokrasi terpimpin terjadi mobilisasi massa dan radikalisasi kaum intelektual dalam Front Nasional yang efektif. ‘Sejumlah kampanye nasional paling penting adalah kampanye melawan keberlanjutan kolonialisme Belanda di Papua Barat, kampanye penyatuan Papua Barat ke Indonesia dan kampanye melawan pembentukan negara bagian Malaysia serta kampanye melawan pengaruh-pengaruh budaya Amerika. Bahkan, ada sejumlah kampanye yang menyerukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Amerika, Inggris, dan Belgia’ (hlm. 35–36). Selain itu, perjuangan reforma agraria dan kenaikan upah buruh juga massif.
…
Membicarakan pergolakan gerakan kiri tentu saja tak bisa lepas dari kancah perpolitikan internasional. Max pun menyodorkan fakta intervensi poros kapitalis, terutama Amerika, dalam usaha kup 1965. Dengan mengutip Audrey R. Kahin dan George Mc T. Kahin (Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia, 1995), Max mengungkapkan, ‘pada 1950-an, pemerintahan Eisenhower bahkan memutuskan bahwa, jika diperlukan, mereka akan mendukung terbelahnya Indonesia dan terpisahnya Jawa (yang merupakan basis golongan kiri) dari wilayah lain di negara ini’ (hlm. 60). Max juga mengutip John Roosa yang banyak menyodorkan bukti pembicaraan di lingkaran-lingkaran diplomatik Amerika Serikat, Inggris, dan Sekutu sebagai poros yang membenci perkembangan politik di Indonesia beserta solusinya. ‘Menurut sudut pandang kami, tentu saja, upaya kup PKI yang gagal kiranya merupakan perkembangan paling efektif untuk membalikkan kecenderungan politik di Indonesia,’ demikian kata Howard P. Jones, Duta Besar AS untuk Indonesia, Maret 1995 yang dikutip Roosa (2006) dalam Pretext for Mass Murder (hlm. 61).[5]
…
Buku ini pun rasa rasakan sebagai peta sederhana saja atas kegagalan gerakan kiri di Indonesia. Membaca buku ini cukup memprovokasi saya untuk menelusuri lebih dalam gerakan kiri, kegagalannya di Indonesia pada 1965 berikut ideologi marxisme yang diusungnya di buku dan artikel-artikel yang memang mengulasnya secara terperinci. Sebagai pembaca pemula gerakan kiri, saya pun sangat berharap, ke depannya bakal semakin banyak penerjemahan karya-karya indonesianis lain, baik buku maupun artikel tentang sejarah 1965, macam karya Benedict Anderson misalnya. Tentunya itu akan sangat membantu warga macam bapak saya untuk perlahan mau merenungi bahwa PKI itu tak bengis sebagaimana diyakininya, justru memihak kaumnya (tani!). Karena, sebagaimana bangsa ini yang dinilai Max Lane belum selesai, malapetaka 1965 memang belum usai.”
- Max Lane, Unfinished Nation: Ingatan Sejarah, Aksi Massa, dan Sejarah Indonesia
- Yang Belum Terselesaikan
Kristian Dwi Nugraha – 18 Desember 2014
Sumber: https://www.balairungpress.com/2014/12/yang-belum-terselesaikan/
“…
Enam puluh empat tahun merdeka, negeri muda ini belum tentu kemana arahnya. Ini belum selesai, Bung!!!
Revolusioner – revolusioner agung tergopoh-gopoh bersimbah darah berlarian menuju medan perang perubahan. Bekal untuk pasca perang terlupakan. Setelah kemenangan, jangankan pesta, hidup layak pun hanya angan. Revolusi, revolusi dan sepertinya belum bosan dengan kosakata itu. Revolusi hanya dipandang seperti ledakan bom atom yang seketika menghapus penghalang. Sering kali terlewatkan proses panjang dan sulit yang terjadi sebelumnya. Bahkan setelah main show, semua hanya terkagum dengan efek destruktifnya. Tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Asal hancur, asal berubah saja, perubahan yang asal.
Seperti itulah Max Lane menggambarkan perubahan dalam buku Unfinished Nation edisi terbaru tahun 2014 terbitan Djaman Baroe ini. Buku ini dibagi menjadi tiga pembahasan, pertama peran sejarah beserta elemen – elemen menuju terciptanya perubahan. Yang kedua, proses perubahan dan terakhir, kemungkinan – kemungkinan pasca perubahan. Perubahan di sini dititikberatkan pada reformasi tahun 1998 yang dikupas mendalam berdasar sejarah pergerakan massa sebelumnya.
…
Buku ini mencoba menempatkan sejarah Reformasi sebagai diskursus baru. Berpijak pada materialisme historis khas Marxisme, reformasi tampil setelah proses yang panjang. Reformasi dibidani oleh gerakan pelopor dengan mobilisasi dan aksi massanya. Penulis menyuguhkan aksi massa yang sering tersisihkan sebagai bagian yang tak terpisahkan sejarah Indonesia. Sangat jarang peran massa diangkat dalam karya sejarah, apalagi dengan perspektif kritis.
Buku ini disusun dengan metode dialektika dan observasi partisipatif. Dengan berdasarkan riset mendalam dan keterlibatan langsung penulis bersama tokoh sejarah perubahan, Pramoedya dan Rendra. Meskipun sebagai buah pengalaman bersama, karya ini tidak menghilangkan sisi kritisnya terhadap para tokoh perubahan. Pengaruh kedekatan dengan dua tokoh tersebut justru memberi unsur sastra pada karya ini. Unsur sastra tersebut tidak hanya sebagai penghias seperti karya sejarah lainnya, namun sebaliknya ia hadir sebagai tubuh dan data penopangnya. Dan hal – hal inilah yang menjadikan buku ini berbeda dengan karya – karya sejarah lainnya.
…
Pada akhirnya, karya ini adalah rujukan yang bagus untuk melihat sejarah Indonesia dengan cara yang berbeda. Sasaran buku ini tidak hanya sejarawan dan akademisi, melainkan siapapun yang peduli dengan sejarah Indonesia.”
- “Indonesia Bangsa yang Belum Selesai?”
Candra Kusuma – 13 Agustus 2015
Sumber: https://haicandra.blogspot.com/2015/08/indonesia-bangsa-yang-belum-selesai.html
“…
Jika umum dipahami bahwa perubahan sosial di sebuah negara akan dipengaruhi oleh faktor endogen (internal) dan exogen (eksternal) dalam perubahan sosial, maka Lane meyakini bahwa faktor endogen, yakni adanya desakan rakyat dari sebuah proses mobilisasi massa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok pelopor, merupakan faktor yang paling dominan dalam mendongkel Soeharto dari tiga dekade lebih kekuasaannya. Dalam hal ini Lane menganggap dirinya mengajukan analisis berbeda dari mayoritas analis Barat yang mengidentifikasi bahwa kekuatan luar negeri atau elitlah yang mejadi penyebab utama kejatuhan Soeharto.
“…Soeharto tidak sekedar jatuh dari kekuasaan–dia didorong jatuh. Gerakan yang mendorongnya jatuh dari kekuasaan berkembang sebagai hasil dari upaya yang sengit (sulit) dan sadar untuk membangun gerakan politik yang benar-benar bisa menjatuhkan sang diktator dan karenanya, dalam tindakannya berbasiskan pada mobilisasi massa rakyat.” (Hal.19)
Menurut Lane, aktor utama yang melakukan pendidikan politik, radikalisasi, dan mobilisasi kalangan kaum miskin, buruh, tani dan mahasiswa adalah para aktivis dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang kemudian berubah menjadi Partai Pembebasan Rakyat (PPR). Lane memang juga menyebutkan beberapa aktor lain seperti Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Pemuda Sosialis, atau koalisi “dadakan” kelompok aksi mahasiswa yang baru muncul dan dibentuk pada 1998 macam Forum Kota (Forkot), namun perannya dipandang lebih kecil.
…
Namun Lane juga menyayangkan bahwa aksi-aksi yang berpuncak di 1998 tersebut tidak dapat membawa gerakan ke arah selanjutnya (hal. 294). Lane tidak menyatakan dengan tegas, namun mungkin dapat dikatakan bahwa PRD “gagal” meyakinkan gagasan mereka pasca turunnya Soeharto, yakni membangun kekuasaan dari bawah sebagai hasil dari proses mobilisasi, sekaligus melakukan penyingkiran semua elit politik Orde Baru. Sementara, menurut Lane, di kalangan aktivis mahasiswa lain berkembang konsep yang campur aduk, yang salah satu dan kemudian menjadi arus utama adalah mengkonsentrasikan arah perubahan pada figur-figur elit politik yang luas dan tidak termasuk atau dicap Orde Baru, khususnya Amien Rais, Abdurrahman Wahid dan Megawati (hal. 282-283).
…
Di bagian akhir bukunya tersebut, Lane memetakan tujuh karakter situasi yang diyakininya memberikan kemungkinan bahwa akan terjadi lagi politik masa yang agresif di Indonesia. Ketujuh situasi tersebut berkenaan dengan: kemiskinan dan kesenjangan sosial yang akut; terbangunnya kesadaran kelas; tumbuhnya kelas pekerja yang professional dan teroganisir; meluasnya penyebaran gagasan kritis; tumbuhnya gerakan politik non-partai berbasiskan demokrasi dan kiri; adanya kelompok-kelompok aktivis dan kader yang berpengalaman; dan makin lazimnya terjadi mobilisasi massa dari kalangan buruh dan miskin kota (hal.507-511).
Bagi Lane, Indonesia adalah bangsa yang belum selesai (unfinished nation). Karena itu, gerakan perubahan diyakininya akan dan harus terus berlangsung. Tujuannya tetap, yang menurut Lane, yaitu dapat menggantikan sistem dan mengukuhkan bentuk pemerintahan demokratik baru yang radikal.
Lane tampaknya memang memiliki posisi yang unik diantara para Indonesianis lain saat ini. Dia meyakini dan optimis bahwa perubahan sosial yang radikal dapat terjadi di Indonesia. Edward Aspinall dalam komentar singkat di sampul belakang buku ini bahkan menyebut Lane sebagai Indonesianis yang “berdiri diluar kesepakatan para ahli” di Australia.”
- Indonesia di Mata yang Berbeda
Tidak Terlacak
Sumber: https://arsipkanlah.blogspot.com/2016/05/resensi-unfinished-nation.html
“…
Max Lane ingin menceritakan kepada pembaca bahwa ternyata kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil dari perang – perang bersenjata para tentara dan hasil perjuangan politis para pendiri bangsa seperti yang diceritakan dalam buku – buku sejarah di sekolah – sekolah. Namun juga hasil dari pemogokan – pemogokan, aksi unjuk rasa yang dilakukan kaum buruh dan tani di Indonesia. dan kaum buruh dan tani juga mempunyai peranan penting dalam usaha indonesia merdeka. Dalam bukunya Max Lane menjelaskan bagaimana buruh perkebunan Sumatra, buruh pelabuhan Batavia dan petani di Jawa Barat Bangkit dan membentuk syarikat – syarikat untuk mobilisasi massa demi kepentingan mereka.
Selanjutnya buku ini bercerita mengenai gagasan – gagasan para pendiri bangsa yang juga melakukan perjuangan yang menggunakan media media seperti koran, poster, pidato – pidato dan rapat akbar sebagain senjata untuk menyebarkan gagasan revolusi. Sampai pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai kemerdekaannya, walaupun kemudian harus berperang secara gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda.
Ketidak sukaan Max lane terhadap sistem Serikat pada Negara Indonesia yang baru merdeka terlihat ketika ia mengungkapkan bahwa sistem tersebut hanya menjadi peluang bagi Belanda untuk kembali merebut pengaruh melalui wilayah – wilayah yang mempunyai kedekatan dengan Belanda.
…
Buku ini lebih banyak berbicara tentang pertikaian antara Angkatan Darat dan Soekarno bersama PKI yang dianggap memihak pihak kiri. Sampai pada Soekarno lengser dan Soeharto mengambil alih kepemimpinan negara melalui surat perintah sebelas maret (supersemar) setelah terjadi penculikan beberapa jendral yang diduga didalangi oleh PKI. Yang akhirnya membuat PKI dilarang dan dalam beberapa buku yang mendokumentasikannya menyatakan adanya pembunuhan masal yang dilakukan oleh ABRI dan ormas Islam sayap kanan yang diperkirakan mencapai korban 500 ribu hingga 2 juta orang. Teror yang diyakini penulis bukan saja harus dilihat untuk membabat habis sayap kiri yang terorganisir, PKI dan kelompok lainnya melainkan teror tersebut untuk mengakhiri revolusi nasional yang diyakini kelompok tersebut belum selesai.
Penulis menyebut gerakan tersebut dengan kontra revolusi gerakan dimana bukan saja untuk menghentikan suatu kelompok yang radikal namun juga semua gagasan – gagasannya yang revolusioner. Hal tersebut bisa dilihat ketika pada masa kepemimpinan Soeharto sebagai presiden yang disebut orde baru banyak ditemukan slogan – slogan kebencian terhadap PKI seperti “ganyang PKI”, Komunisme itu berarti anti tuhan, dan ajaran Marxisme dan leninisme juga dilarang pada massa itu. Dalam pelajaran – pelajaran sejarah pun diperlihatkan bahwa PKI adalah pengkhianat yang ingin menghancurkan bangsa indonesia. Film layar lebar yang mempropagandakan hal tersebut diwajibkan ditonton oleh pelajar dan ditayangkan setiap minggu. Bahkan keluarga atau bekas tahanan politik mempunyai simbol yang membedakan mereka dalam kartu tanda penduduknya (KTP). Suatu propaganda yang masif untuk menghapuskan sebuah ideologi di Indonesia yag dilakukan secara terorganisir dan menghapuskan ingatan sejarah tentang perjuangan mereka yang membantu mewujudkan kemerdekaan Indonesia.”
- Indonesia and Not, Poems and Otherwise: Anecdotes Scattered
- Kenangan Max Lane
Arif Koes – 26 Maret 2017
Sumber: https://arifkoes.wordpress.com/2017/03/26/kenangan-max-lane/
“Pulau Dewata, 1969. Pemuda Sydney, Australia, berumur 17 di akhir tahun pertama kuliahnya itu tiba di Bali. Dengan naik mobil jip, ia berpetualang keliling desa-desa, melintasi sawah, berselancar di Pantai Kuta yang masih dikunjungi 20-an orang.
Namun dari petualangan itu, setelah bertemu warga desa, petani, dan orang-orang miskin di sana, Max mempelajari satu hal. Indonesia memiliki kata “rakyat” yang tak serta merta bisa diterjemahkan sebagai “people”, melainkan kata yang secara khusus bermakna “the people as againts the elite”. “Di Australia tidak ada kata ‘rakyat’,” kata Max.
Itulah kenangan Max Lane saat pertama kali mengunjungi Indonesia yang begitu membekas dan dituangkan di buku terbarunya, Indonesia and Not, Poems and Otherwise: Anecdotes Scattered. Peluncuran buku ini digelar secara sederhana, dengan mengundang rekan-rekan dan kolega Max, di toko buku Periplus, Mall Malioboro, Yogyakarta, medio Desember, tahun lalu.
…
“Tulisan di buku ini tentang ingatan pada adegan-adegan yang tidak luput dari otak saya karena nuansa antara Australia dan Indonesia, juga empati pada rakyat kecil. Akan garing banget jika memahami dengan analis politik doang. Puisi lebih bebas,” tutur Max kepada Gatra.”
- Pradipto Niwandhono, Yang Ter(di)lupakan: Kaum Indo dan Benih Nasionalisme Indonesia
- Sisi Lain dari Sejarah, Review Buku Yang Ter(di)lupakan: Kaum Indo dan Benih Nasionalisme Indonesia
Uswatun Hasanah – 30 Jun 2023
“…
“Yang Ter(di)lupakan; Kaum Indo dan Benih Nasionalisme Indonesia yang ditulis oleh Pradipto Niwandhono merupakan sebuah buku yang membahas kajian menarik yang cukup sering muncul dalam kepustakaan Belanda namun kondisi sebaliknya terjadi di Indonesia. Padahal pokok pembahasan menyangkut sepenuhnya pada keberlangsungan sejarah nasionalisme Indonesia. Kaum Indo-Eropa agak diabaikan dalam historiografi Indonesia.
…
Kepustakaan yang dipakai dalam buku Yang Ter(di)lupakan; Kaum Indo dan Benih Nasionalisme Indonesia relatif tua. Yang menarik ialah keseluruhannya bukan berasal dari kepustakaan Indonesia. Jadi kajian mengenai komunitas Indo-Eropa dengan perspektif penulis Indonesia bisa dibilang baru. Terbukti dengan sangat kesulitannya untuk menemukan kajian lain terkait komunitas Indo-Eropa berbahasa Indonesia kecuali buku karya Pradipto Niwandhono.
Inilah letak keunggulan dari buku Yang Ter(di)lupakan; Kaum Indo dan Benih Nasionalisme Indonesia. Pradipto Niwandhono bisa menyajikan interpretasi baru terhadap posisi kaum IndoEropa bagi historiografi Indonesia. Terlebih lagi, buku ini berhasil membeberkan fakta menarik mengenai benih-benih nasionalisme yang muncul justru akibat dari kecemburuan sosial.
…
Kesadaran bertahap itu bermula dari konsep sederhana yang bersikukuh bahwa tanah airnya ialah Hindia Belanda. Secara psikologis, jiwa mereka berpihak kepada tanah air yakni Hindia Belanda sehingga bekerjasama dengan kalangan pribumi untuk tujuan bersama menjadi hal wajar. Kesadaran tersebut mengalami transformasi menjadi benih-benih nasionalisme.
Atribut-atribut hibrida menuai kesadaran atas identitas komunal masyarakat Indis yang semakin terintegrasi berkat rangsangan dari isu-isu diskriminasi ras. Kebudayaan Indis dan komunitas pendukung (Kaum Indo-Eropa dan kalangan priyayi Jawa) adalah produk dari sejarah panjang kolonialisme Belanda. Indis berurat akar dari kata Indisch (Indie atau Hindia) yang mengacu pada daerah koloni bangsa Belanda di kepulauan Nusantara.
Sebagian besar sumber primer tidak memuat unsur emosional tokoh sejarah dari kaum Indo-Eropa baik Douwes Dekker maupun Karel Zaalberg. Akan tetapi, Pradipto Niwandhono dalam bukunya ini berhasil memunculkannya. Adanya ketidaksepahaman antara dua tokoh pergerakan dari kaum Indo-Eropa yakni Karel Zaalberg dan Douwes Dekker menjelaskan bahwa perjuangan tidak selamanya selaras serta bersifat homogen tanpa pertentangan.”
- Max Lane, Indonesia Tidak Hadir di Bumi Manusia: Pramoedya, Sejarah dan Politik
- Kata Max Lane, Indonesia Tidak Hadir di Bumi Manusia
Satyaadhi – 11 Noember 2024
Sumber: https://medium.com/@satyaadhi/kata-max-lane-indonesia-tidak-hadir-di-bumi-manusia-ea836917d3e3
“…
“DOSA BESAR!” Katamu lantang, tenang.
Sialan. Suaramu itu membuat seratusan orang terhenyak. Mereka, yang baru saja membeli bukumu seharga 59 ribu, dipaksa menahan napas.
Kau melanjutkan celoteh. “Sastra Indonesia, pemikiran Indonesia sejak Kartini sampai ’65 tidak diajarkan di sekolah-sekolah menengah. Apakah memang saat ini pun Indonesia masih tidak hadir di Bumi Manusia?”
Hari itu, 12 Agustus 2017, para hadirin di Galeri Cipta III, Taman Ismail Marzuki, Jakarta — termasuk aku — akan dipaksa bertanya-tanya. “Siapa yang berdosa?”; “apakah yang tidak berdosa otomatis suci?”; “mengapa Indonesia tidak hadir di Bumi Manusia?”; “bagaimana cara menghadirkannya?”
Orang yang sudah membaca buku kumpulan esaimu akan tahu jawababannya.
Mereka bakal tahu kalau Adam Malik pernah berkata bahwa Tetralogi Pulau Buru sebaiknya jadi bacaan wajib buat semua pelajar sekolahan. Saat itu Adam Malik menjabat Wakil Presiden. Sayang, perkataannya tak pernah jadi ujud.
Ironi yang melankoli. Di luar Republik, sumbangsih pemikiran Pramoedya bagi kajian sejarah Indonesia mulai diakui. Kau menulis kalau Tetralogi Pulau Buru didaftarkan di mata kuliah universitas di negeri nun jauh sana. Karya-karya itu juga masuk dalam wacana intelektual mengenai sastra dunia dan studi-studi pascakolonial.
Sejarawan pada umumnya akan mudah berkata, bahwa memang di awal abad 20 istilah “Indonesia” belum ada. Tapi kau menguraikannya dengan lebih jeli. Kau tahu bahwa Pramoedya tidak menghadirkan Indonesia di Bumi Manusia dengan penuh kesadaran dan kesengajaan.
Tidak hadirnya Indonesia di Bumi Manusia, sekaligus menolak semua sejarah versi bangku sekolah. Di buku pelajaran sejarah, Indonesia dikhultuskan sebagai titisan suci Sriwijaya dan Majapahit. Padahal, Indonesia tercipta dari penolakan terhadap masa lampau yang feodalistik cum kolonialistik cum kapitalistik.”
- Memahami Pesan Terselubung Pram soal Indonesia
Hera Khaerani – 26 Agustus 2017
Sumber: https://mediaindonesia.com/humaniora/119441/memahami-pesan-terselubung-pram-soal-indonesia
“…
Akan tetapi, bukan hanya larangan pemangku kekuasaan yang bisa menjauhkan masyarakat dari pemikiran sejati seorang Pram. Banyak pula yang sudah membaca karyanya, tapi gagal memahami pesan terselubung yang ingin disampaikan sang penulis. Hal inilah yang ingin disoroti Max Lane dalam buku terbarunya, Indonesia tidak Hadir di Bumi Manusia. Pesan terselubung Pram diyakininya harus disadari masyarakat dalam menghadapi masa depan Indonesia. Penulis dan kritikus asal Australia itu menawarkan hasil analisisnya lewat esai dan artikel yang dikumpulkan dalam buku tersebut. Sesuai dengan judul bukunya, Max mengajak masyarakat untuk turut merenungi mengapa dalam tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, Pram tidak pernah sekali pun menulis kata Indonesia di dalamnya.
Bagi Max, absennya ‘Indonesia’ di Bumi Manusia justru menjadi gagasan fundamental yang menunjukkan kegeniusan seorang Pramoedya Ananta Toer sekaligus menjadi pembelajaran berharga bagi rakyat Indonesia saat ini untuk memahami apa itu Indonesia. Pramoedya bagi Max Lane hendak menegaskan soal kebaruan Indonesia. ‘Bukan hanya bahwa Indonesia adalah barang ciptaan baru di atas muka bumi manusia ini. Bukan hanya baru, tetapi ternyata juga barang atau makhluk ciptaan sendiri! Seri buku Bumi Manusia sampai Rumah Kaca menggambarkan proses di saat penghuni sebuah tempat tertentu, yang bangkit mulai memakai bahasa tertentu, menciptakan sendiri sebuah komunitas baru: menuju sebuah nation’, tulisnya dalam halaman 170.
Menolak gagasan keindonesiaan
Pramoedya menolak gagasan keindonesiaan yang kerap dilabuhkan ke masa lampau tradisional. Indonesia tidak hadir sebagai suatu kesinambungan dengan masa lampau, justru berupa penolakan terhadap masa lampau. Hal ini terlihat misalnya ketika ibunda Minke (karakter dalam novelnya) ditampilkan mengucapkan kata-kata, “Mengapa engkau mencoba begitu keras untuk menjadi selain dari anak ibumu?” Berbicara dalam peluncuran dan diskusi buku terbarunya oleh Dewan Kesenian Jakarta di Galeri Cipta III Taman Ismail Marzuki (12/8), Max pun menceritakan selama perkenalannya dengan Pramoedya semasa hidup, tidak pernah sekali pun dia mendengar Pram menggunakan bahasa daerah. “Dia selalu pakai bahasa Indonesia,” ungkapnya menekankan bahwa itu bukti kecintaan Pram yang tinggi terhadap Indonesia yang turut dia perjuangkan kemerdekaannya.
…
Organisasi adalah sebuah karakter baru di dalam Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Karakter ini disebut baru bukan karena tidak kelihatan di kedua novel pertamanya, melainkan karena sebelum organisasi-organisasi seperti yang dilukiskan dalam Jejak Langkah dan Rumah Kaca muncul, di ‘Indonesia’ memang sama sekali tidak ada organisasi-organisasi modern. Kepada Max, Pram pernah menegaskan bahwa kalau mau mengubah masyarakat, harus ada alatnya, harus ada wadahnya untuk pertarungan ideologi melawan ketidakadilan. Wadah yang dimaksud adalah organisasi.
Karena itu, budaya berorganisasi menurut penulis Unfinished Nation tersebut adalah budaya Indonesia. Jika masyarakat masa kini tidak terbiasa berorganisasi apalagi bersikap antipati, itulah wujud meninggalkan budaya Indonesia yang sesungguhnya. Simpulan itu diambilnya tidak hanya dari pergumulan bertahun-tahun menerjemahkan karya Pram, tetapi juga hasil diskusi langsung dengan Pram, dengan orang-orang yang berani menerbitkan karyanya, juga pengalamannya sendiri bergaul dengan banyak aktivis di Indonesia. Memahami pesan Pram soal Indonesia itu relevan saat ini, terutama ketika ada pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah.”
- Max Lane, Saudara Berdiri di Pihak yang Mana? Politik Seni Subversif Rendra
- Subversivitas Ambiguitas
Dhianita Kusuma Pertiwi – Jul 14, 2024
Sumber: https://dhiandharti.medium.com/subversivitas-ambiguitas-9c6111a7263d
“Maksud baik Anda untuk siapa?
Saudara berdiri di pihak yang mana?”
Dua larik “Sajak Pertemuan Mahasiswa” yang ditulis W.S. Rendra tersebut –paling tidak menurut saya– mempunyai umur daya tampar yang panjang, jika tidak abadi. Hanya saja, dalam konteks dunia kesusastraan Indonesia saat ini, jika ada seorang penyair yang membuat puisi bernada serupa, ia akan dicemooh karena menulis ‘puisi pamflet’. Rendra sendiri sebenarnya juga sudah mendapatkan cemooh demikian pada 1970-an, dan ia meresponsnya secara cukup tangkas dengan menyuarakan “Pamflet bukan tabu untuk penyair”¹ serta mengumpulkan tulisan tangan puisinya lalu dijilid dan difotokopi dengan judul Pamflet Penyair. Semua itu ia lakukan untuk semakin mempertegas posisi — politik — nya sebagai seorang penyair, khususnya di bawah rongrong otoritarianisme Orde Baru.
Posisi itu jugalah yang berusaha dibaca Max Lane melalui bukunya, Saudara Berdiri di Pihak yang Mana?: Politik Seni Subversif Rendra yang merangkum beberapa tulisan pembacaannya atas karya-karya dan proses kreatif Rendra terutama sebagai seorang dramawan. Banyak pembahasan penting dalam buku tersebut yang membantu saya untuk lebih memahami karya-karya drama Rendra yang bisa dibilang cukup berjarak dari saya.
…
Dengan semua situasi tersebut, saya mendapati terbitnya tulisan-tulisan Max Lane tentang karya dan kiprah Rendra sebagai salah satu momentum pencerahan dalam ranah kajian sastra, khususnya kajian terhadap karya-karya drama dan teater. Meski demikian, agaknya karena buku ini merupakan kumpulan tulisan yang sebelumnya dipublikasikan secara terpisah-pisah, tidak terlalu mudah untuk mengikuti dan memahami alur pembahasan dan argumen-argumen yang disampaikan penulisnya. Beberapa bagian menunjukkan repetisi, seperti misalnya uraian terkait posisi Rendra ketika polemik politisasi sastra vs humanisme universal terjadi. Pada saat yang sama, sejumlah konsep dan argumen yang dihadirkan sebagai kerangka dan hasil pembacaan atas karya Rendra tersebar di sepanjang buku layaknya daun kering yang gugur dan berserakan.
…
Di tengah kondisi seperti ini, Max Lane menawarkan cara pembacaan yang segar dengan menjadikan elemen dari karya Rendra sebagai kerangka pembacaan. “Saudara berdiri di pihak yang mana?” diterjemahkan kembali oleh Max Lane sebagai pertanyaan yang perlu disampaikan untuk membaca posisi politik Rendra berdasarkan karya-karya dan aktivitas berkeseniannya. Secara tidak langsung, Max mengutarakan bahwa pengulas karya sesungguhnya memiliki keleluasaan yang sedemikian luas dalam membaca karya atau sosok penulis yang dihadapinya. Hal ini akan membawa kita kembali kepada esensi kritik sastra yang bukan perkara salah benar yang diujikan berdasarkan rumus-rumus pasti, melainkan sebuah dialog pertanggungjawaban atas suatu pernyataan. Kita tidak selalu harus berlindung di balik tameng pendapat orang lain–yang kebetulan namanya lebih besar– karena suatu karya bisa menawarkan ruang eksplorasi yang sangat luas. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjelajahi ruang-ruang tersebut. Oleh karena itu, keputusan analitik yang diambil Max Lane dapat dan perlu dipelajari oleh mereka yang tertarik pada pengkajian dan kritik sastra.
…
Saya pun cukup setuju dengan pernyataan Max Lane bahwa “karya Rendra dan sumbangannya terlalu berharga untuk tidak menjadi milik seluruh rakyat Indonesia”.² Meski demikian, minat dewasa ini terhadap karya-karya Rendra, baik untuk sekadar dinikmati, ditampilkan, atau dibaca secara kritis, bisa dibilang tidak terlalu tinggi. Hal ini berkaitan dengan isu struktural yang sempat saya utarakan pada awal tulisan ini. Di sisi lain, saya juga berasumsi kurangnya minat ini turut dipengaruhi oleh dinamika gelombang (baca: tren) estetika dalam penciptaan karya sastra dan seni–perihal yang akan saya bahas lebih lanjut pada bagian berikutnya dalam tulisan ini.
…
Kita akan mendapati argumen-argumen Max Lane atas karya dan kiprah Rendra tersebar di sepanjang buku Saudara Berdiri di Pihak yang Mana?: Politik Seni Subversif Rendra, yang semuanya mengarah pada jawaban atas pertanyaan “Saudara berdiri di pihak yang mana?” Mari kita lihat kembali lini masa perjalanan Rendra yang saya rangkum di atas, dimulai dari periode sebelum 1965.
…
Setelah tuntas membaca buku Max Lane, saya dibayang-bayangi oleh pertanyaan bagaimana menentukan posisi berdiri di pihak yang mana di era serba kontemporer saat ini. Era ketika pemaknaan serba relatif dan diwarnai dengan gejala-gejala budaya baru yang kemunculannya turut dipengaruhi oleh terbentuknya ekosistem digital. Era ketika –seperti beberapa orang utarakan– sulit untuk menentukan musuh bersama layaknya Angkatan 66 yang berhadapan dengan pemerintah Sukarno dan Angkatan 98 yang berada di posisi antagonistik dengan Orde Baru. Era ketika estetika pamflet dianggap nomor dua setelah sajak-sajak liris yang mengaduk-aduk sisi romantik dari benak pembaca. Era ketika masih ada ekses-ekses dari pendefinisian ‘revolusi’ sebagai subversif sehingga hanya menjadi kosakata sekelompok orang terbatas.
Bukan perkara mudah untuk menjawab perihal tersebut tetapi–sekali lagi–barangkali, kita bisa kembali ke “Sajak Pertemuan Mahasiswa”, bahwa di antara semua ambiguitas, “ada yang jaya, ada yang terhina / ada yang bersenjata, ada yang terluka / ada yang duduk, ada yang diduduki / ada yang berlimpah, ada yang terkuras”; dan dalam hal ini kita masih perlu berpikir dan bertindak subversif, serta berdiri di pihak yang terluka, diduduki, dan terkuras.”